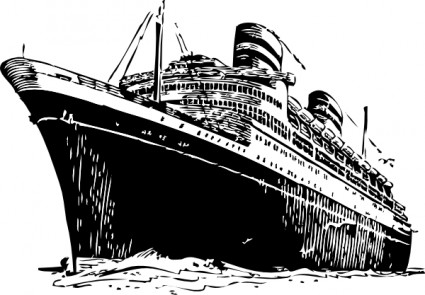Oleh: Musliha Rofiq
Migrasi sering kita maknai sebagai proses berpindahnya seseorang atau komunitas dalam waktu yang lama, dari suatu tempat ke tempat yang lain melintasi batas administratif (daerah) dan batas politik/Negara (internasional) baik untuk tujuan menetap maupun untuk bekerja, demi untuk keberlanjutan hidup. Kultural atau budaya adalah tradisi yang dipegang teguh secara turun temurun, prosesnya terjadi berulang-ulang. Praktik-praktik kultural dalam masyarakat terkandung sebuah nilai dan prinsip yang diyakini secara umum sebagai sesuatu kebenaran yang dipertahankan secara bersama di suatu komunitas, berdasarkan suku, kebangsaan atau keyakinan tertentu.
Berpindahnya manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain sudah merupakan esensi dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dalam perkembangan sejarah, bentuk dan polanya selalu berubah dari waktu ke waktu, dinamis/ tidak statis (monoton). Tanah harapan/tanah tujuan adalah gapaian untuk masa depan.
Masyarakat Indonesia juga mengenal praktik migrasi secara kultural sejak lama bahkan sebelum konsep administrasi negara modern berlangsung (perbatasan/paspor/visa). Beberapa komunitas di Indonesia memiliki praktik migrasi kultural yang berakar kuat antara lain komunitas Madura, Bugis, Bajau, Padang-Minangkabau, Banjar, Bawean, Sasak, Flores dan beberapa komunitas lainnya. Praktek migrasi secara turun temurun dan dilakukan secara sukarela ini banyak dibahasakan oleh para pakar dengan migrasi swadaya atau migrasi mandiri.
Berbagai alasan bermigrasi secara swadaya selain alasan klasik untuk memperbaiki nasib juga bersentuhan dengan sistem dan situasi yang sedang berlaku di suatu daerah atau komunitas tertentu. Kalau bisa kita urai misalnya masyarakat Madura, Bugis dan Minangkabau yang banyak kita temui di berbagai titik daerah atau di luar negeri memiliki motif migrasi untuk menjawab tantangan alam (tanah tandus, sering ada bencana alam/gempa, gunung meletus dll), ketika alam sudah tidak bisa menjanjikan maka mereka akan bermigrasi ke tempat yang lebih menjanjikan. Bermigrasi juga dilakukan dengan alasan untuk merubah kondisi kehidupan keluarga yang lebih baik: misalnya pendidikan anak, pembiayaan keluarga dan mendapat tempat tinggal yang layak. Baru belakangan alasan dengan besaran gaji dibanding tempat asalnya menjadi alasan untuk bermigrasi.
Sejak akhir dekade tujuhpuluhan dan menjelang dekade delapanpuluhan, pemerintahan Orde Baru berupaya memformalkan proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanisme ekonomi, menggunakan pihak swasta (non state actor) untuk mengatur mulai soal rekrutmen dan penempatannya ke luar negeri. Pola baru yang diperkenalkan ini secara perlahan namun pasti untuk menggeser pola migrasi tenaga kerja berbasis kultural yang telah lama berlangsung dalam mengintervensi peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan Indonesia. Puncak pengingkaran total terhadap realitas migrasi kultural (migrasi swadaya) yang ada dalam masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan adanya pasal-pasal kriminalisasi terhadap praktek migrasi kultural/migrasi swadaya dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Disisi yang lain UU ini memberikan monopoli paripurna terhadap peran swasta (aktor non negara) dalam soal tata kelola penempatan buruh migran Indonesia. Sangatlah berisiko menyerahkan nasib manusia yang bekerja sebagai manusia hanya dengan mendelegasikan kepada aktor non negara (dalam hal ini Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS) yang orientasi utamanya melipatgandakan keuntungan.
Tidak terakomodasinya praktek migrasi kultural/migrasi swadaya dalam tata kelola penempatan buruh migran Indonesia serta buruknya tata kelola penempatan buruh migran berbiaya tinggi dibawah kontrol PPTKIS berdampak pada tingginya praktek migrasi beresiko dalam bentuk perdagangan manusia (human trafficking).
Keberanian masyarakat untuk berpindah secara swadaya, mandiri dan sukarela melintasi batas negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan dari pola migrasi di Indonesia yang sudah berjalan sangat lama. Migrasi secara kultural ini seharusnya diatur dalam sebuah kebijakan yang mengakui keberadaan mereka. Mengakomodasi migrasi swadaya akan mengeliminasi praktek-praktek kriminal dan eksploitasi yang terkandung dalam migrasi swadaya.
Tidak ada jaminan ketika pemerintah mempromosikan migrasi aman hanya melalui jalur PPTKIS, buruh migran tidak akan menemui masalah ketika bekerja di luar negeri. Dari data kasus buruh migran yang diperoleh dari institusi pemerintah dan organisasi non pemerintah (termasuk Migrant CARE) menunjukkan bahwa PPTKIS adalah aktor predatoris bagi buruh migran, mulai dari tahapan perekrutan, pelatihan hingga upaya-upaya pengambilan keuntungan tidak sah melalui praktek pemotongan upah dan pembiaran masalah yang dihadapi buruh migran.
Dalam upaya memberi masukan untuk proses revisi dan perubahan yang lebih baik bagi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, DPR-RI dan Pemerintah Indonesia harus membuka ruang diskusi untuk mengakhiri praktek diskriminasi dan kriminalisasi terhadap migrasi swadaya yang masih berlangsung dibeberapa tempat.
Sebagai sebuah pola migrasi yang masih berlangsung, migrasi swadaya harus diakomodasi dan dipastikan menjadi salah satu praktek migrasi aman dengan membentenginya dari upaya-upaya jahat sindikat perdagangan manusia memboncenginya dan memastikan kehadiran negara ada untuk menjamin rasa aman.