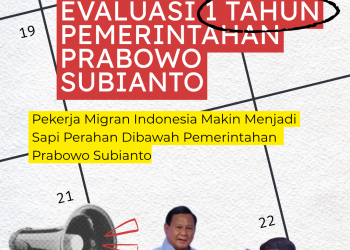Di awal tahun 2020, Migrant CARE melalui Migrant CARE Outlook 2020 telah memprediksi bahwa kecamuk COVID-19 akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap dinamika migrasi tenaga kerja international, tak terkecuali pada pekerja migran Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, episentrum awal virus Korona (yang kemudian di tanggal 11 Maret 2020 resmi ditetapkan sebagai pandemi COVID-19) berada di kawasan Asia Timur dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Kawasan ini adalah negara-negara tujuan para pekerja migran Indonesia seperti Hong Kong, Taiwan, daratan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura. Dampak langsung merebaknya virus Korona dialami oleh para pekerja migran Indonesia di kapal-kapal pesiar yang bergerak di lautan antar negara. Sebagian besar di antara mereka harus berhenti bekerja, mengalami isolasi dan karantina dengan segala risiko yang dihadapinya.
Para pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan inilah yang sejatinya menjadi korban pertama paparan virus Korona dan dampak sosial-ekonominya. Mereka menghadapi langsung kenyataan kelangkaan masker dan panic buying yang memaksa mereka harus berkerumun dan antre di pusat-pusat perbelanjaan dengan risiko tinggi terpapar virus jahat ini. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga juga semakin terbebani dengan jam kerja yang bertambah, waktu istirahat yang berkurang, namun terancam pada pengurangan upah dan rentan mengalami kekerasan berbasis gender.
Pekerja migran juga rentan mengalami stigmatisasi (sebagai pembawa virus), diskriminasi (sebagai warga asing) dan kriminalisasi akibat kebijakan pembatasan mobilitas yang mengawasi secara ketat pergerakan manusia, apalagi pergerakan antar negara yang mengalami pengetatan total sejak bulan Maret 2020.
Pemberlakuan Movement Control Order (MCO) di Malaysia juga berkontribusi besar pada ketidakpastian nasib jutaan pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Karena status kerjanya sebagai pekerja upah harian dan mingguan, otomatis mereka kehilangan pekerjaan, terjauhkan dari akses kesehatan dan rentan mengalami penangkapan akibat penerapan Operasi Benteng, sebuah kebijakan represi pemerintah Malaysia dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
Hal yang patut mendapat perhatian serius adalah arus kepulangan pekerja migran yang berlangsung secara massif sepanjang awal masa pandemi COVID-19 yang bersamaan dengan masa mudik Lebaran. Pada awalnya, terjadi penumpukan di terminal kedatangan bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Juanda dan Pelabuhan Batam akibat kelangkaan moda transportasi menuju kampung halaman selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Situasi ini akhirnya diatasi Gugus Tugas yang memberi diskresi pengadaan moda transportasi ke kampung halaman sekaligus penerapan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak terjadi pembentukan kluster penularan COVID-19 dari proses pemulangan pekerja migran di kampung halaman.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia terlihat tidak memiliki kesiapan dalam mempersiapkan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kebijakan perdana yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan RI menghadapi pandemik ini hanya ditujukan untuk pekerja sektor formal dan abai pada pekerja di sektor informal dan pekerja migran. Hal ini tampak terlihat dari kebijakan mengenai pemberian subsidi upah hanya untuk mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Kebijakan mengenai penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia karena COVID-19 melalui Kepmenaker 151/2020 tidak dibarengi dengan langkah antisipasi di lapangan. Sehingga para calon pekerja migran yang gagal berangkat masih ada yang tertahan di penampungan, mengalami ketidakpastian bahkan harus membayar uang jaminan untuk dapat pulang ke kampung halaman.
Derasnya arus pemulangan yang mencapai lebih dari 166 ribu pekerja migran Indonesia juga tidak dibarengi dengan kesiapan yang mendekatkan mereka pada akses jaring pengaman sosial atau stimulan untuk mereduksi dampak COVID-19. Menurut asesmen yang dilakukan Migrant CARE di beberapa daerah basis pekerja migran, sebagian besar para pekerja migran yang pulang semasa pandemik tidak bisa memperoleh bantuan sosial dampak COVID-19 karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data penyaluran bantuan sosial.
Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan baik di negara asal maupun negara tempat pekerja migran Indonesia juga makin menghambat akses keadilan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah termasuk untuk korban perdagangan manusia. Pemberian layanan secara daring (online) meski menjadi salah satu solusi, namun tidak semaksimal hasilnya dibandingkan dengan layanan langsung (offline). Pengurangan layanan kekonsuleran dan pembaruan dokumen yang dilakukan perwakilan RI di luar negeri juga memberi dampak langsung pada pekerja migran yang mengalami masalah di negara tempat bekerja. Kementerian Sosial bahkan menghapus mata anggaran pemberdayaan ekonomi untuk korban perdagangan manusia, atas nama refocusing anggaran dampak COVID-19.
Pekerja migran Indonesia juga merupakan kelinci percobaan dari penerapan kebijakan penempatan pekerja migran di masa new normal. Dengan Kepmenaker 294/2020, kebijakan penghentian sementara dicabut dan penempatan pekerja migran dibuka kembali meski kurva kasus COVID-19 di Indonesia masih menanjak dan gelombang kedua kasus COVID-19 terjadi lagi di negara-negara tujuan. Di Jepang dan Taiwan bahkan ditemukan kasus pekerja migran Indonesia yang terindikasi positif COVID-19 sesaat setelah tiba di negara tersebut.
Hingga memasuki tahun ketiga berlakunya UU No. 18/2017, belum ada kemajuan yang signifikan dari implementasi UU ini. Tata kelola baru migrasi tenaga kerja yang berorientasi pelayanan publik tak kunjung terbentuk karena belum ada landasan kebijakan turunan tentang kewenangan pemerintah daerah hingga desa untuk menjadi bagian penting dalam tata kelola ini.
Tahun 2020 ini juga merupakan tahun kelam bagi pekerja migran Indonesia di sektor kelautan, terutama yang bekerja sebagai anak buah kapal ikan berbendera asing. Kasus pelarungan 3 jenazah ABK di kapal berbendera Tiongkok membuka kotak pandora praktik perbudakan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan. Ironisnya, walau UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan adanya kebijakan pelindungan untuk mereka, namun hingga saat ini aturan turunannya tak kunjung muncul.
Kasus perdagangan manusia, kekerasan berbasis gender yang berujung pada kematian serta kriminalisasi terhadap pekerja migran tidak berdokumen juga terus berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih dijumpai adanya kasus perdagangan manusia ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah bahkan juga ke negara-negara terlarang karena konflik bersenjata (Libya dan Suriah). Penyiksaan keji yang dialami oleh EH, pekerja migran asal Cirebon yang bekerja di Malaysia seperti mengulang kasus Adelina dan Nirmala Bonat. Walau jelas nyata kekerasan itu terjadi, namun keadilan masih jauh didapat dan pelakunya menikmati impunitas. Kasus-kasus tersebut merupakan puncak gunung es dari kasus-kasus pekerja migran Indonesia senyatanya yang tak terhitung.
Sebaliknya, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tak lepas dari ancaman para pengeruk keuntungan dari bisnis penempatan pekerja migran dengan melakukan judicial review pasal-pasal pengetatan persyaratan perusahaan pengerah pekerja migran dan pengenaan sanksi pidana untuk pelanggarannya. Walau akhirnya judicial review ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, namun UU ini masih tetap terancam lumpuh oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selain itu juga ada upaya penjegalan pembahasan proses legislasi yang mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia yang mayoritas perempuan seperti RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Alih-alih mendorong tata kelola baru migrasi yang berorientasi perlindungan, pemerintah Indonesia bersama parlemen malah melakukan akrobat legislasi dengan menerbitkan Omnibus Law UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berpotensi melumpuhkan spirit perlindungan yang ada dalam UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanpa kesipan tata kelola migrasi tenaga kerja yang baru, inisiatif BP2MI menerbitkan kebijakan zero cost penempatan pekerja migran tampaknya sia-sia karena tidak ada infrastruktur yang memadai.
Hal-hal lain yang berpengaruh pada komitmen pelindungan pekerja migran Indonesia adalah belum adanya indikator-indikator nasional yang tercantum dalam Peta Jalan Pencapaian SDGs dan metadata SDGs Indonesia terbaru terkait tata kelola migrasi dan upaya penghapusan perdagangan manusia. SDGs sebagai komitmen global yang memiliki berbagai target dan goal yang terukur untuk mengakhiri perdagangan manusia dan mewujudkan tata kelola migrasi yang aman seharusnya juga bisa menjadi panduan perencanaan kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia serta upaya penghapusan perdagangan manusia. Komitmen global yang juga diadopsi oleh Indonesia sejak tahun 2018 adalah Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Indonesia juga selalu mengklaim aktif dalam mempromosikan kesepakatan global ini dengan keterlibatan Menteri Luar Negeri RI sebagai Cho-Chair. Namun hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki Rencana Aksi Nasional untuk untuk GCM. Dalam pandangan Migrant CARE, Rencana Aksi Nasional GCM ini setidaknya bisa mengkonsolidasi perspektif hak asasi manusia dan tata kelola migrasi yang aman untuk implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Jakarta, 18 Desember 2020
Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE
[email protected]