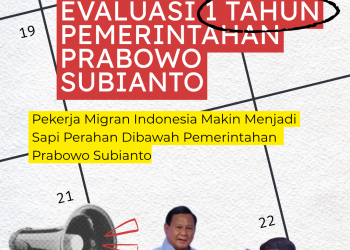The rising of the women means the rising of the race No more the drudge and idler, ten that toil where one reposes But a sharing of life’s glories: Bread and Roses, Bread and Roses. ~ James Oppenheim (1882-1932), Bread and Roses
Teori demokrasi yang dijukstaposisikan dengan feminisme akan mengkritik politik arus utama. Politik mainstream tersebut punya metodologi maskulin yang berwatak phallus yang hanya mencari kekuasaan dan melupakan substansi sejarah politeia. Kini ia bernafaskan kepentingan yang menghasilkan kemandekan dialektika soal kesejahteraan dan sebagainya. Ditambah politik klientelisme yang menjadikan politik sebagai alat sekumpul elitis.
Sulit ditemui narasi tentang kewarganegaraan dan kemerdekaan. Apalagi HAM dan kemartabatan. Padahal, politik dengan identitas demokrasi seharusnya menjadi jembatan antara negara dan rakyatnya untuk dapat mencapai keadilan dengan iklim yang tak represif. Sebuah republik yang jauh dari asas tersebut terlihat sedang mencari cara untuk menghapus politik dari usaha res-publica. Pertanyaannya kini, mengapa perempuan kurang terwakili dalam politik? Mampukah kita berbicara tentang demokrasi ketika perempuan tidak sepenuhnya ada dalam pengambilan keputusan politik?
Pemilu tahun 2019 ini diramaikan oleh figur perempuan yang akan duduk di parlemen. Bagi kultur patriarkis, perempuan hanya ada di ruang privat. Tak pantas di ruang publik. Sehingga politik yang ada di lokus publik hanya milik laki-laki. Dengan begitu, dominasi dimungkinkan. Perempuan yang terjun dalam politik menjadi harapan besar bagi narasi feminisme dan keadilan sosial dalam ruang politik. Meski begitu, perempuan dalam legislasi harus tetap diskrutinisasi. Apakah ia memiliki visi untuk isu perempuan? Apakah ia sekadar dikultuskan oleh dinasti politik yang oligark?
Agenda politik dengan keputusan afirmasi bahwa perempuan harus mendapatkan kuota 30% mungkin progresif di Pemilu tahun 2014. Tetapi bila lima tahun telah berlalu dan pemenuhan kuota masih jadi urusan formalitas, tentu ini menjadi sebuah kemunduran. Tubuh politik tak bicara tentang formalitas. Tubuh politik tak berbicara kuantitatif atas kuota untuk kampanye yang serba dangkal. Lebih dari itu, politik harus kembali pada ideologi demokrasi yang egaliter dan berbasis HAM. Dengan konsekuensi logisnya yang akan menghasilkan keadilan yang adil dan beradab. Tak terkecuali pada siapapun dan tak sebaliknya.
Seorang pendukung HAM akan serta-merta menjadi seorang demokratis. Namun, seorang demokratis tak membuatnya menjadi seorang pendukung HAM. Kekhawatiran ini muncul saat ide demokrasi dilepas menjadi wacana yang tak terpadu. Situasi ini yang kemudian membentuk kekosongan ruang yang status-quo nya bisa diputarbalikkan oleh politik kekuasaan yang dinikmati para aktor dengan maksud tertentu. Maksudnya, emblem demokrasi diidentikkan dengan bentuk kebebasan yang jauh dari kemawasan. Contohnya ada pada keleluasaan kaderisasi partai yang tak bersih, bermahar, hingga pencalonan seorang eks-koruptor. Padahal, pengaderan khususnya untuk jabatan politik harus dilakukan seterbuka mungkin. Momen pemilihan umum yang sering dikatakan sebagai pesta demokrasi masih dihadapkan pada situasi para pemilih yang masih jauh dari ketercukupan informasi dan kemampuan berpikir. Pesta demokrasi akan sekejap menjadi pesta mobokrasi. Kerentanan tersebut bagi kelompok politik yang sebatas memikirkan kekuasaan dengan kaderisasi kepartaian yang buruk, akan memanfaatkan keadaan hampa semacam ini.
Demokrasi telah mengecewakan perempuan. Politik tak hanya bertahan pada arus utamanya dengan hanya laki-laki sebagai yang-politis, tetapi juga telah melewati tindakan non-etis. Sejatinya, kebenaran dan kekuasaan bisa berarti sebuah kontemplasi besar jika perspektif etik masuk di dalamnya. Demokrasi membutuhkan gairah pemikiran yang setara dan egaliter. Ini yang kemudian membuat Pemilihan Umum lebih cocok dibilang perjuangan ketimbang sebuah pesta.
Kendati secara riil demokrasi berujung tombak pada sistem elektorat, bukan mengiyakan bahwa demokrasi hanya bersubstansi pada perjuangan partai politik untuk memenangkan kuota untuk masuk ke parlemen. Menihilkan aspek perjuangan sipil marginal dalam pencapaian keadilan adalah kemunduran. Kita harus bisa mencapai titik dimana politik bukan sekadar soal konstitusi. Yang kita lihat hari-hari ini, standar demokrasi terus turun ke titik nol. Kian menjauhkan perempuan dan kelompok paling tertinggal untuk dapat menikmati akses keadilan dalam bentuk apapun. Ditambah hierarki politik yang oligarkis semakin menutup narasi feminisme dan kepentingan perempuan dalam agenda politik. Indonesia membutuhkan kedamaian dan harapan yang ada untuk hari esok. Pemimpin perempuan yang bisa mewakili suara yang tak terdengar. Pemimpin yang memiliki analisis kuat untuk berbicara kesejahteraan dan keadilan sosial.
Setidaknya disini kita masih sepakat akan dua hal: masuknya perempuan dalam parlemen adalah agenda feminis, bukan feminisasi alat politik. Sebab perempuan adalah tentang identitas gender yang penuh dengan pergulatan power-over, bukan tentang jenis kelamin. Kedua, keterwakilan perempuan dalam tubuh politik adalah standar bagi sebuah negeri yang mengaku demokratis. Seperti puisi Oppenheim di atas; demokrasi tak hanya untuk kesejahteraan–metafor dari sepotong roti atau Bread, namun juga harus untuk cinta-kasih dan penghargaan martabat perempuan, seumpama bunga atau Roses.
Artikel ini telah dipublikasikan di laman Jurnal Perempuan, 26 Maret 2019.